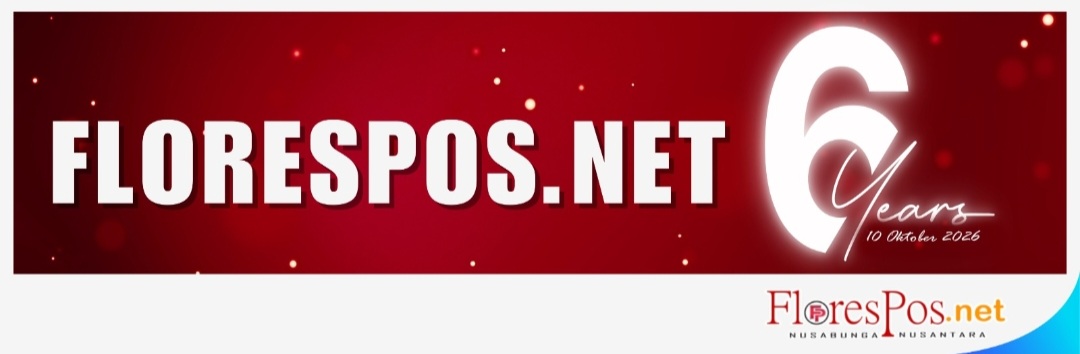Oleh: Florentina Ina Wai
LIRIK lagu Sal Priadi tentang “titik-titik di ujung doa” terasa pedih saat ini. Kalimat itu menjadi nyata bagi para pejuang nafkah di Indonesia.
Di tengah narasi Indonesia Emas 2045, jutaan pekerja justru terjebak dalam ketidakpastian. Guru, tenaga medis, dan pegawai honorer sedang mengeja harapan di ruang tunggu yang sangat lama. Harapan mereka kini berhadapan dengan gunting efisiensi negara yang tajam dan dingin.
Dulu kita percaya bahwa ‘rajin pangkal kaya’. Pepatah ini menjadi pegangan hidup masyarakat kita. Suku Madura, Minang, dan Bugis adalah contoh nyata dari etos kerja ini. Bagi mereka, kerja keras adalah bentuk ibadah kepada Sang Pencipta. Mereka hidup hemat dan ulet karena percaya pada hasil dari sebuah proses.
Data statistik juga menunjukkan hal yang luar biasa. Tingkat partisipasi angkatan kerja kita mencapai 70,63 persen pada tahun 2024. Mayoritas penduduk kita adalah pekerja penuh waktu. Produktivitas tenaga kerja pun terus meningkat setiap tahun. Angka-angka ini membuktikan bahwa rakyat Indonesia memiliki kemauan tinggi untuk membangun ekonomi.
Namun, muncul sebuah kenyataan yang menyakitkan di lapangan. Rakyat bekerja sangat keras, tetapi negara justru memangkas harapan mereka melalui kebijakan efisiensi. Saya melihat fenomena ini sebagai ‘ketangguhan yang beracun’. Masyarakat dipaksa memiliki daya tahan tinggi namun hak mereka dipotong atas nama penghematan anggaran. Ini adalah bentuk eksploitasi keringat rakyat yang mengabaikan hak hidup bermartabat.
Dalam manajemen sumber daya manusia, kondisi ini disebut pelanggaran kontrak psikologis. Rakyat memberikan loyalitas dan dedikasi kepada negara. Sebagai gantinya, negara seharusnya memberikan perlindungan dan kesejahteraan. Kebijakan penghapusan jalur pengabdian dalam seleksi pegawai adalah bentuk pengkhianatan kontrak sosial. Hal ini memicu hilangnya motivasi kerja secara massal.
Mari kita lihat perbandingan upah dengan negara tetangga. Pendidik di Malaysia bisa membawa pulang belasan juta rupiah. Di Singapura, angkanya bahkan menembus puluhan juta rupiah. Sementara itu, banyak dosen dan guru di Indonesia masih menerima gaji dua hingga lima juta rupiah saja. Perbedaan ini sungguh menyesakkan dada para pahlawan tanpa tanda jasa kita.
Pemerintah harus segera membenahi kebuntuan ini. Praktik menuntut pengabdian tanpa batas tanpa kepastian regulasi harus dihentikan. Negara wajib membangun kembali kepercayaan publik melalui kebijakan yang transparan. Lingkungan kerja yang pasti sangat penting bagi kesehatan mental para pekerja. Kesejahteraan guru dan tenaga medis adalah kunci kemajuan bangsa.
Selain itu, negara harus mulai melihat upah sebagai investasi strategis. Upah layak akan memicu produktivitas yang jauh lebih tinggi. Cara ini juga bisa menekan angka korupsi karena kebutuhan dasar pekerja sudah terpenuhi. Efisiensi anggaran seharusnya menyasar birokrasi yang boros. Jangan sampai upah manusia yang menjadi sasaran pemotongan biaya.
Manajemen talenta nasional juga butuh desain ulang. Seleksi pegawai harus menghargai masa pengabdian pekerja. Penghapusan tenaga honorer tanpa melihat rekam jejak saya pandang sebagai sebuah kesalahan. Sistem negara harus mengakui dedikasi nyata selama bertahun-tahun sebagai komponen utama kesejahteraan.
Doa para pekerja tidak boleh berakhir menjadi titik mati karena kebijakan yang kaku. Kita harus berhenti menganggap kemiskinan sebagai hal normal dalam pengabdian. Etos kerja hebat dari rakyat harus dijawab dengan sistem negara yang adil. Efisiensi tanpa kemanusiaan hanyalah bentuk lain dari penindasan. Kerja keras di negeri ini harus membuahkan kesejahteraan, bukan kelelahan yang sia-sia. *
Penulis adalah Staf Publikasi dan Jurnal Ilmiah Stipar Ende